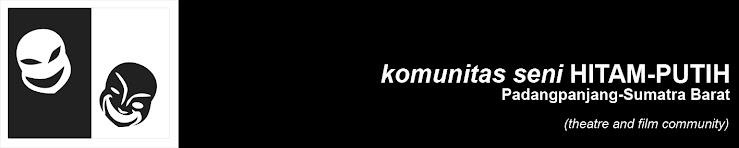Oleh Sahrul N
Benny Yohannes dalam makalahnya mengatakan bahwa “multikulturalisme dalam teater seyogyanya dipahami dalam prinsip hadir yang selalu tidak ada (absent present). Bahwa budaya itu tidak pernah memiliki transendensi atau Pengada-Besar, atau asal-usul arkaiknya. Sebab pelacakan terhadap asal-usul seperti itu selalu membikin kita yatim dan semakin yatim. Namun rentangan keyatiman itu adalah sumber-sumber epistemik yang tak pernah menyediakan batas, kefinalan atau kesudahan”.
Benny mengungkapkan pikirannya dalam seminar PAT 2003. Selain Benny juga ada Azuzan JG dari IKJ Jakarta, Sahrul N dari STSI Padangpanjang, dan Zulkifli dari STSI Padangpanjang yang membicarakan multikulturalisme teater Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Selain seminar juga ada pertunjukan teater yang diikuti sebanyak 6 kelompok teater yang terdiri dari IKJ Jakarta, STSI Bandung, Teater Prung Bandung, Teater Sastra Unand Padang, Teater IAIN Imam Bonjol Padang, dan STSI Padangpanjang sebagai tuan rumah. Semua peristiwa ini hadir mulai dari tanggal 15 s/d 20 Mei 2003 di STSI Padangpanjang.
Teater adalah suatu peristiwa atau memperjelas peristiwa. Naskah, keinginan sutradara, kemampuan pemeran, artistik, panggung dan lain-lain hanyalah unsur-unsur dalam membangun peristiwa yang pada akhirnya menuju pada dialektika antara hal-hal yang diharapkan dengan yang tak disangka-sangka. Perpaduan unsur-unsur tersebut menjadikan teater membuka ruang yang sangat luas terhadap adaptasi budaya. Tak ada yang tak mungkin dalam dunia kreativitas teater.
Multikulturalisme ada yang memahaminya sebagai penekanan terhadap ras yang mengacu pada keanekaragaman yang menunjukan keharmonisan, namun mengabaikan masalah bahasa dan budaya. Akibatnya justru akan menimbulkan konflik seperti Indonesia saat ini. Untuk itu konsep multikulturalisme harus dimaknai sebagai reaksi yang meliputi budaya, bahasa yang ditinjau secara lebih rinci terutama yang berkaitan dengan munculnya kekuatan dominasi antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Arahnya adalah keseimbangan antara kepentingan etnik tertentu dengan etnik yang lain yang saling berinteraksi.
Pertunjukan dalam rangka PAT diawali oleh kelompok Teater IAIN Imam Bonjol Padang yang mengusung naskah Karbala 2 karya / sutradara Zelfeni Wimra c.s. Dalam konteks multikultural, pertunjukan Karbala 2 mengambil semangat perang Karbala untuk kepentingan pemahaman dari peristiwa sejarah. Idiom-idiom Timur Tengah dipadukan dengan konsep dramaturg dari Barat serta ditambah sentuhan tradisi Minangkabau menjadikan adanya pergulatan kebudayaan dari masing-masing etnis yang bersentuhan tersebut. Perang Karbala hanyalah titik berangkat cerita tetapi bukan fokus utama. Begitu juga dengan konsep penggarapan yang mengambil konsep-konsep Barat dan kemudian dipadukan dengan konsep tradisi Minangkabau menjadikannya kaya akan idiom-idiom atau simbol-simbol etnis yang berbeda.
Berbeda dengan yang ditampilkan Teater KMT STSI Bandung yang membawa naskah Bui karya Akhudiat, sutradara Firman dalam bentuk absurd. Menjadikan karya realisme dalam bentuk absurd merupakan pencarian ruang lain dan pemaknaan yang berbeda. Penjara tidak lagi bermana fisikal tetapi sudah menjadi makna epistemik. Makna yang lebih dalam serta penggambaran yang simbolis. Naskah Bui hanya mengadirkan tokoh dua orang, akan tetapi dalam pertunjukan ini, sutradara menghadirkan satu tokoh yang lain (sipir penjara) untuk memberikan makna yang berbeda. Usaha ini merupakan usaha dalam mencari beraneka ragam (multikultural) pemahaman dalam mencari identitas atau tanpa identitas.
Teater Prung mencari cara lain dalam mengangkat Perempuan Memalu Batu, karya Tim Prung, sutradara: Hikmat Gumelar Berdoa. Berbeda dengan konsep estetika panggung selama ini (panggung teater konvensi) lakon Perempuan Memalu Batu menghilangkan fokus. Fokus pada setiap adegan seperti diserahkan kepada jangkauan tatapan dan ketertarikan oleh penonton secara bebas. Pertunjukan dimulai dengan kemunculan para pemain dari sudut kanan belakang pentas. Kostum pemain dibalut dengan kain berwarna hitam (satu pemain perempuan) sementara selebihnya dibalut dengan lilitan kain putih. Beberapa beberapa pemain laki-laki mencat kepalanya dengan warna hitam dan merah. pertunjukan berlangsung dalam tempo yang monoton dan kaku. Properti yang begitu memenuhi pentas terkesan hanya menjadi benda-benda mati. Tak ada cerita, tak ada kisah. Yang ada hanya peristiwa dan monolog pemain.
Teater Langkah Fakultas Sastra Unand Padang menampilkan Meja Makan Kita karya M. Syafari Firdaus, sutradara Hariyanto Prasetyo. Tiga dewa (Brahma, Wisnu, dan Syiwa) dipakai untuk mengungkapkan persoalan kekinian dan mempertegas bahwa dalam kehidupan selalu ada kebajikan dan kejahatan. Pengambilan simbol masa lalu (babad) untuk kepentingan pertunjukan hari ini merupakan usaha multikulturalisme yang mengarah pada pembunuhan identitas untuk membentuk identitas baru.
Sementara Teater KMT STSI Padangpanjang menggarap Barabah karya Motinggo Busye, sutradara Wen Hendri yang murni memakai konsep realisme tetapi makna yang disampaikan mencoba untuk melampaui realisme itu sendiri. Banio sebagai laki-laki yang memiliki banyak istri memiliki kecenderungan membanggakan keperkasaannya. Sama halnya dengan laki-laki zaman sekarang atau yang terlihat pada anak muda hari ini. Laki-laki selalu menyelesaikan sesuatu lewat kekerasan. Begitu juga dengan tokoh Barabah yang menyimbolkan seorang perempuan yang tidak mau dimadu seperti halnya perempuan-perempuan sebelumnya. Emansipasi dan gender merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan Barabah.
Sama halnya dengan Teater KMT STSI Padangpanjang, Teater KMT IKJ Jakarta membawa konsep realisme dengan naskah Pinangan karya Anton P. Chekov, sutradara Hestu Wreda. Pertunjukan yang verbal ini membuat penonton tidak terlalu berpikir menganalisa persoalan. Apalagi kemampuan ketiga pemeran yang cukup berhasil dengan improvisasi kocak. Kekonyolan ketoprak dan lenong masuk dalam wilayah teater realisme Brehctian, begitu juga dengan memasukan unsur Minangkabau, ketika Agus pingsan (disangka mati oleh Ratna). Ratna menyanyikan lagu Minang yang sangat sedih sambil diringi oleh bansi (musik etnis Minangkabau), betul-betul kekonyolan yang luar biasa.
Multikulturalisme merujuk pada proses kerjasama, interaksi dan persilangan antar kelompok budaya. Silang budaya memperoleh dimensinya yang baru berkenaan dengan persentuhan yang intensif antar kebudayaan baik karena proses globalisasi maupun revolusi media. Taufik Rahzen berpendapat bahwa persentuhan antar budaya, tidak saja melampaui batas-batas geografis, tetapi juga bersilangan dalam dimensi waktu yaitu bergerak ke masa lampau dan masa depan. Pemadatan ruang dan waktu dalam proses silang budaya, membongkar kelaziman transmisi nilai yang biasanya diwariskan generasi ke generasi.
Teater masing-masing etnis berbeda-beda sesuai dengan sifat kebudayaan secara umum. Karena itu, perubahannya pun menjadi berbeda-beda. Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan di dalam teater tertentu mencakup sampai seberapa jauh sebuah komunitas teater mendukung dan menyetujui adanya fleksibilitas, kebutuhan-kebutuhan teater itu sendiri pada waktu tertentu, dan yang terpenting adalah tingkat kecocokan di antara unsur-unsur baru dan matriks teater yang ada. Perubahan teater dapat berjalan dengan lamban, agak lama, dan cepat.
Teater di Indonesia saat ini merupakan refleksi kebhinekaan yang sangat besar. Faktor geografis dan historis menghalangi perkembangan teater yang homogen dengan arah garis evolusi yang tunggal. Fenomena keberagaman budaya hadir dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda. Sebagian ada yang menjadikan teater tradisi (etnis tertentu) sebagai basic untuk mengungkapkan idiom-idiom hari ini. Pada bagian yang lain ada yang menjadikan teater sebagai ungkapan yang universal, sehingga etnisitas tidak begitu menonjol atau hampir hilang sama sekali.
Dalam rangkaian kesatuan pertumbuhan teater, unsur-unsur lama dan baru tumpang tindih, bercampur baur, atau kadang-kadang hadir berdampingan. Angka-angka tahun hanyalah merupakan pembagi perkiraan yang menandai adanya perkenalan ide-ide atau teknik baru, tanpa perlu dijelaskan tentang lenyapnya kepercayaan-kepercayaan serta kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Untuk itu perlu adanya pembaharuan sudut pandang dalam mengamati teater sebagai seni pertunjukan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada pertunjukan teater yang dilakukan pada PAT 2003 ini. Tradisi dan modernitas hanyalah alat untuk mengukur jangkauan kreativitas seniman dalam melahirkan karya teater.
Perubahan dimensi waktu dan jarak bukan saja mempertinggi tingkat keseringan dalam perkunjungan tetapi lebih penting lagi mengecilkan rasa keasingan. Artinya perbedaan antara mana yang kita dan mana yang mereka makin mengabur. Dalam suasana seperti ini, ketika komunikasi telah berjalan lebih lancar bukanlah hal yang terlalu aneh, dan ini merupakan akulturalisme yang memberi makna keberagaman.
Wacana multikulturalisme bukanlah otonom. Bukan pula sebuah permainan yang adil, yang sejauh ini pada prakteknya dimungkinkan lewat pertukaran dengan dasar yang tidak adil. Sampai hari ini multikulturalisme berlanjut untuk dijadikan teori, retorika, konsep, kerangka, dan peta, hampir di seluruh dunia. Akhirnya PAT 2003 di STSI Padangpanjang membuka ruang pemikiran tentang multikulturalisme teater Indonesia dan mencoba untuk menghormati kehadiran yang berbeda pada kelompok teater di Indonesia. Seperti yang dikatakan Benny bahwa teater mengungkap “yang lain” (the other)***